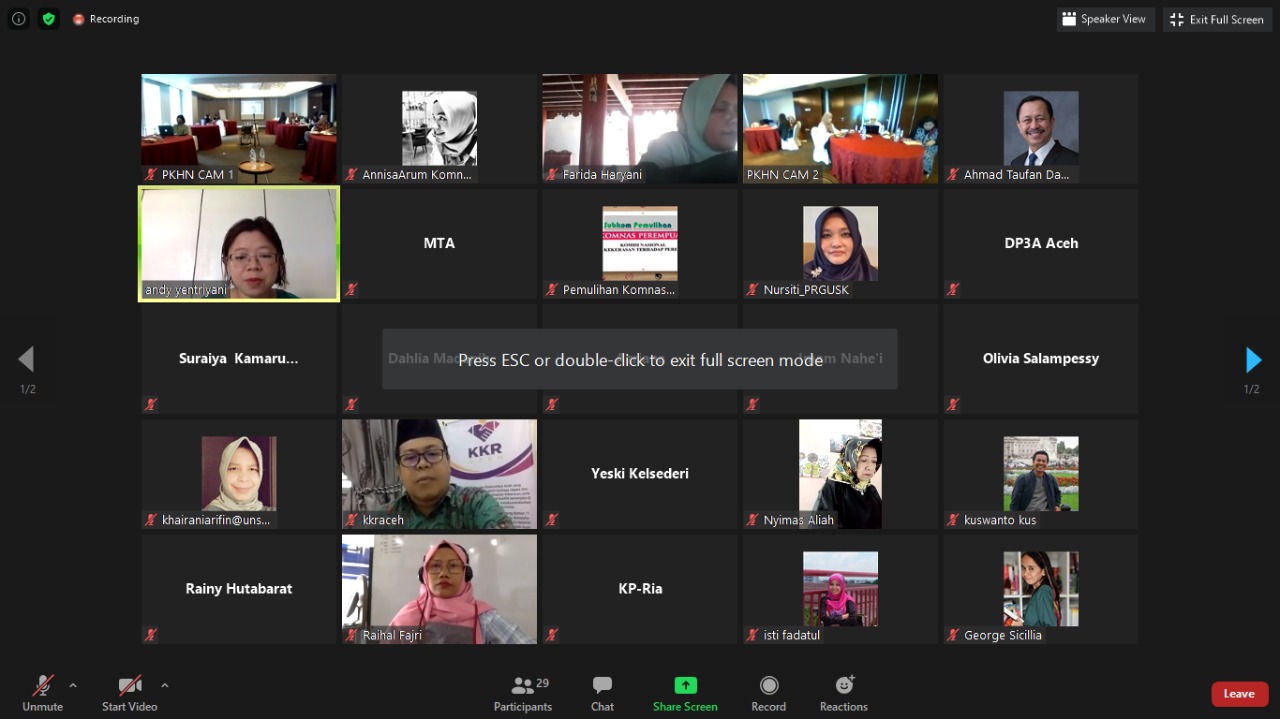
Latuharhary – Lima belas tahun pasca penandatangan perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, banyak harapan perbaikan bagi kehidupan masyarakat Aceh terbuka lebar.
Selain mengakhiri konflik, butir-butir kesepakatan perdamaian nyatanya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Beberapa di antaranya penyelesaian peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan pemenuhan hak-hak korban. Persoalan mengenai perempuan dan anak juga mewarnai Aceh pasca kesepakatan.
Perkembangan terbaru berdasarkan kajian lembaga swadaya masyarakat, salah satunya oleh Balai Syura Ureung Inong, saat ini timbul kerentanan bagi perempuan dan anak di Aceh. Kebijakan dan aturan yang diskriminatif dinilai memperkuat budaya patriarki, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya perlindungan terhadap perempuan korban kekeresan seksual, dan meningkatnya konflik sosial, konflik agraria, dan sumber daya alam.
“Alih-alih menjawab persoalan korban konflik, di tengah kondisi pasca perdamaian dan tegaknya demokrasi lokal di Aceh, justru tumbuh kerentanan baru dengan adanya perda-perda yang rentan diskriminasi dan menyasar kaum perempuan,”ujar Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik
dalam lokakarya bertajuk"Meneguhkan Damai di Aceh berbasis Pengalaman Perempuan Selama 15 Tahun Pelaksanaan Nota Kesepahaman Helsinki" yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan bekerja sama dengan Komnas HAM dan Universitas Syiah Kuala, Kamis (13/8/2020).
Komnas Perempuan juga mencatat bahwa penikmatan perdamaian bagi perempuan menghadapi tantangan yang khas. Isu kekerasan seksual, khususnya, dalam konteks pelanggaran HAM di masa lalu, kini bergantung pada kinerja dan dukungan bagi pelaksanaan rekomendasi KKR Aceh. Kerentanan pada kekerasan juga meningkat, termasuk pada kriminalisasi sebagai dampak dari kebijakan daerah diskriminatif yang kerap sulit didiskusikan dengan mengatasnamakan kewenangan otonomi khusus Pemerintah Aceh.
Kehadiran Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 13 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat yang mengatur sejumlah pasal turut dikritisi karena dinilai melemahkan perempuan korban, terutama pada pidana perkosaan dan pelecehan seksual dalam mencari keadilan.
Mencermati perkembangan terkini, Taufan berharap regulasi dan tata kelola pemerintahan harus mempertimbangkan perspektif perempuan agar tidak ada ketimpangan relasi gender dalam proses transformasi Aceh. Taufan mengingatkan pada para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk juga berpihak dan jangan sampai suara perempuan ditutup dan terabaikan.
“Lantas dimana suara perempuan Aceh selama 15 tahun pasca MOU Helsinki, jika ruang bagi perempuan tertutup maka ini akan menjadi problem baru untuk perempuan dan anak di Aceh,” ucapnya.
Menyoal penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu dan pemenuhan hak-hak korban, Taufan mengkritisi jumlah korban yang menurutnya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Oleh karena itu, ia menagih keseriusan dan langkah konkret berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan berbagai pihak. “Komnas HAM menyerahkan sepenuhnya soal kompensasi. Komnas HAM bertanggungjawab memastikan keadilan dan jalannya proses pengungkapan kebenaran,” tegasnya.
Bagi Taufan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan hutang yang wajib dibayar. Lantaran apapun mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah sebaiknya tidak mengabaikan keadilan bagi para korban dan menghentikan jalannya proses hukum.
“Jangan hanya bermaafan. Permaafan harus dimulai dari pengungkapan kebenaran dan menjalankan proses peradilan atau sejenisnya yang memiliki kekuatan hukum,”pungkasnya. (AAP/IW)
Short link

















